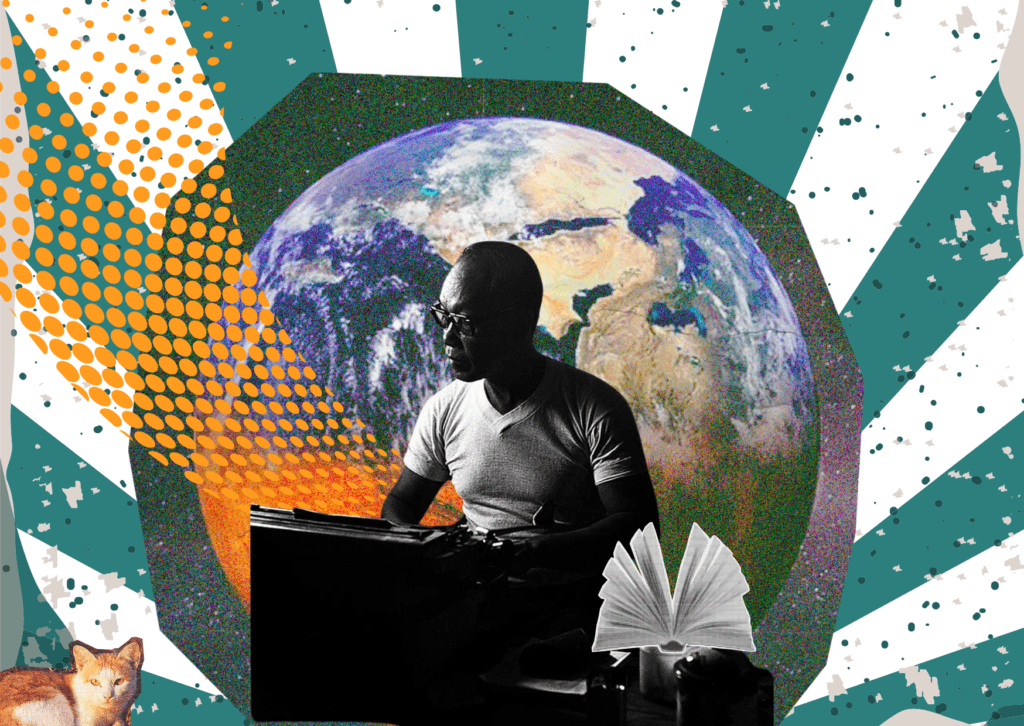Bumi Manusia (1980), karya monumental Pramoedya rajazeus login Ananta Toer, bukan sekadar novel sejarah, melainkan cermin tajam atas ketidakadilan kolonialisme, feodalisme, dan penindasan berbasis ras dan kelas. Lebih berasal dari empat dekade sesudah peluncurannya, kritik sosial didalam novel ini ternyata masih relevan bersama dengan konteks Indonesia modern—mulai berasal dari kesenjangan sosial, kekerasan sistemik, hingga perlawanan pada otoritarianisme.
Sinopsis & Konteks Penulisan
Bumi Manusia adalah buku pertama dari Tetralogi Buru, ditulis Pram semasa ditahan di Pulau Buru (1965–1979) tanpa akses literatur. Novel ini berlatar Hindia Belanda awal abad ke-20 dan mengisahkan kehidupan Minke, pemuda Jawa terpelajar yang terlibat dalam pergulatan identitas, cinta, dan perlawanan terhadap kolonialisme.
Tokoh utama lain, Nyai Ontosoroh, simbol perempuan pribumi yang melawan feodalisme dan rasialisme. Kisahnya menggugah pertanyaan: Bagaimana sistem kolonial dan feodal menghancurkan martabat manusia?
Kritik Sosial dalam ‘Bumi Manusia’
1. Rasialisme dan Diskriminasi Kolonial
-
Hukum Belanda membagi masyarakat ke dalam strata:
-
Eropa (kelas tertinggi).
-
Timur Asing (Tionghoa/Arab).
-
Pribumi (kelas terendah).
-
-
Minke, meski ningrat Jawa dan terdidik, tetap dianggap “inlander” oleh Belanda.
-
Relevansi hari ini: Diskriminasi struktural masih terjadi, misalnya dalam ketimpangan akses pendidikan dan pekerjaan berdasarkan kelas ekonomi.
2. Feodalisme dan Patriarki
-
Nyai Ontosoroh, gundik Belanda yang cerdas, dilabeli “hina” oleh masyarakat Jawa feodal.
-
Perlawanannya melambangkan pemberdayaan perempuan yang harus berjuang di tengah sistem patriarkal.
-
Relevansi hari ini: Perjuangan melawan kekerasan seksual dan stigma terhadap perempuan (misalnya, kasus pelecehan di lingkup kerja/kampus).
3. Kekerasan Sistemik dan Otoritarianisme
-
Pemerintah kolonial menggunakan hukum dan militer untuk membungkam kritik (contoh: pemenjaraan aktivis).
-
Relevansi hari ini: Pola serupa terlihat dalam pembatasan kebebasan berekspresi dan kriminalisasi aktivis.
4. Perlawanan melalui Pendidikan
-
Minke menggunakan tulisan dan media (mendirikan koran) sebagai senjata melawan kolonial.
-
Relevansi hari ini: Gerakan seperti #ReformasiDikorupsi atau aksi mahasiswa 2019 menunjukkan kekuatan literasi dan media sosial sebagai alat protes.
Mengapa ‘Bumi Manusia’ Masih Relevan?
1. Cermin Masalah yang Tak Kunjung Usai
-
Kesenjangan sosial: 1% orang Indonesia menguasai 47% kekayaan nasional (data Oxfam 2023).
-
Korupsi elite: Mirip dengan eksploitasi kolonial, kini dilakukan oleh penguasa pribumi.
-
Represi terhadap minoritas: Diskriminasi terhadap kelompok marginal (Papua, Ahmadiyah) berakar dari mentalitas kolonial.
2. Inspirasi untuk Gerakan Sosial
-
Karakter Nyai Ontosoroh menginspirasi gerakan feminisme Indonesia.
-
Perlawanan Minke melalui tulisan paralel dengan aktivisme jurnalisme warga saat ini.
3. Sastra sebagai Alat Kritik yang Abadi
Pramoedya membuktikan bahwa sastra bisa menjadi “senjata” melawan lupa dan ketidakadilan.
Tantangan Membaca ‘Bumi Manusia’ di Era Modern
-
Bahasa yang padat: Gaya penulisan Pram yang kental dengan istilah historis butuh usaha ekstra pembaca muda.
-
Politik identitas: Sebagian kelompok menolak karya Pram karena dianggap “kiri”, menunjukkan polarisasi politik yang masih hidup.
Kesimpulan
BACA JUGA: Bukan Sekadar Cerita: Novel yang Membuatmu Merenung Lama Setelah Tamat
Bumi Manusia bukan sekadar novel, melainkan manifestasi perlawanan yang terus bergema. Kritik Pramoedya tentang kolonialisme, feodalisme, dan represi masih tercermin dalam ketidakadilan sistemik, oligarki, dan represi kebebasan hari ini.
Membaca ulang karya ini mengingatkan kita: “Sejarah mungkin ditulis oleh pemenang, tetapi kebenaran disuarakan oleh mereka yang berani melawan.”